Minggu depan anak-anak saya masuk sekolah (satu di SMP dan satu di SD), kemarin mereka merengek-rengek ke sekolah untuk mengambil (membeli) buku pelajaran. Lho kenapa nggak pinjam aja teman yang sudah lulus, “udah ganti, jadi bukunya bisa beda pak” kata mereka.
Situasi memang sudah mengarah agar anak-anak membeli buku dari sekolah, “takut beda”.
Di sekolah para guru memang sudah siap dengan buku-buku tersebut, yang SD satu paket Rp 185 ribu, sedang yang SMP satu paket Rp 447 ribu.
Jadi untuk buku aja total Rp 632 ribu. Banyak juga nih. 😦
Kayak apa sih buku-buku tersebut. Tipis-tipis, menurutku nggak ada yang istimewa, yang ngarang aja juga tidak aku kenal. Kayaknya aku juga bisa koq kalau mau. Tapi yang jelas buku tersebut pasti sangat laku dibanding buku-bukuku, karena ada jaminan dibeli oleh siswa.
Aku mengingat sekolahku dulu di Yogya, di SMP atau SD dulu, rasanya tidak ada itu pembelian buku-buku seperti itu yang mahal tersebut. Rasanya buku-buku dulu dipinjamin sekolah atau bisa pinjam dari kakaknya, yang aku ingat yaitu di SMA, buku paketnya dipinjamin. Juga buku paket yang dimaksud tidak sebanyak sekarang, hanya Fisika, Biologi, Matematika, Sejarah dan Bahasa Indonesia. Nggak banyak tetapi tebal dan berbobot. Bukunya juga itu-itu juga. Tidak seperti sekarang, tiap tahun selalu harus baru, buku agama aja ada dua, tipis-tipis lagi, pokoknya bukunya banyak deh, sehingga harganya juga mahal. 😦
Aku merasa sekolah jaman sekarang bertele-tele, tidak efisien, manja, nggak lebih berbobot dibanding jaman dulu tapi yang jelas berbiaya tinggi.
Apa coba alasannya bahwa buku pelajaran setiap tahun harus ganti. Pada tingkat perguruan tinggi aja nggak seperti itu. Itu khan hanya agar menghasilkan uang aja khan. Kalau alasannya biar selalu up-to-dated. Aku mau tahu, siapa sih yang punya pendapat seperti itu. Aku yakin orang tersebut pasti dapat keuntungan materi dengan alasan tersebut.
Pantes sekarang IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) rame-rame berubah menjadi Universitas, misinya GAGAL.
Pantes juga, jika dulu sekitar tahun 50-an (sebelum ada IKIP) banyak guru-guru Malaysia belajar di Indonesia, tetapi sekarang banyak orang kita yang gantian belajar ke Malaysia.
Pantes juga mendengar kabar ada satu kelompok guru-guru PGRI dari Semarang ke Jakarta untuk berdemo menuntut dana pendidikan ke pemerintah. Berdemo ! Jadi nggak beda ya dengan buruh.
Ada indikasi, tapi kayaknya betul bahwa sekolah di Indonesia semakin mahal. Tetapi kondisi tersebut tidak berimbas kepada kesejahteraan guru. Mana ada guru yang sejahtera hidupnya mau bersusah-susah demo ke Jakarta. Meskipun yang demo tersebut mempunyai alasan klasik yaitu untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa, tetapi ujung-ujungnya pasti menyangkut kesejahteraan diri juga. Indonesia…
Iya khan. 😀
Kasihan itu para keluarga Indonesia yang anak-anaknya sedang bersekolah di sini. 😦




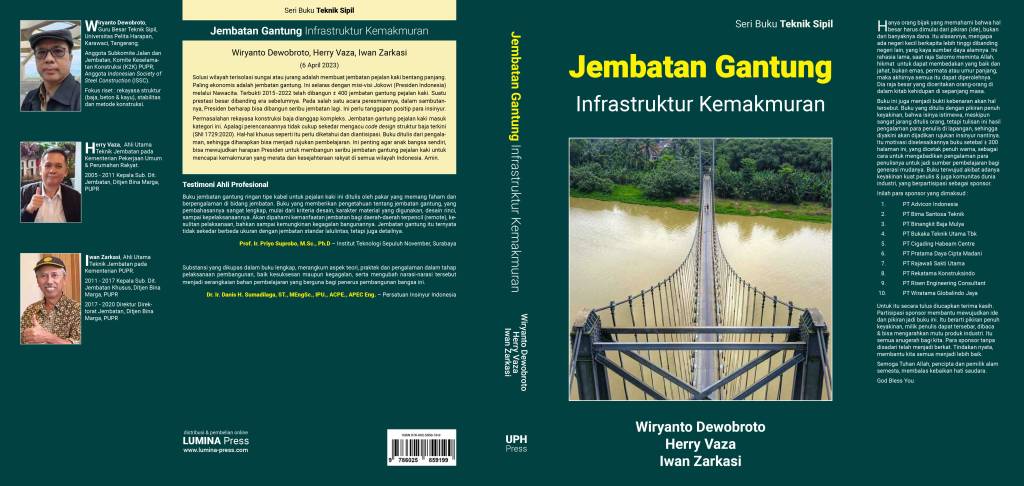

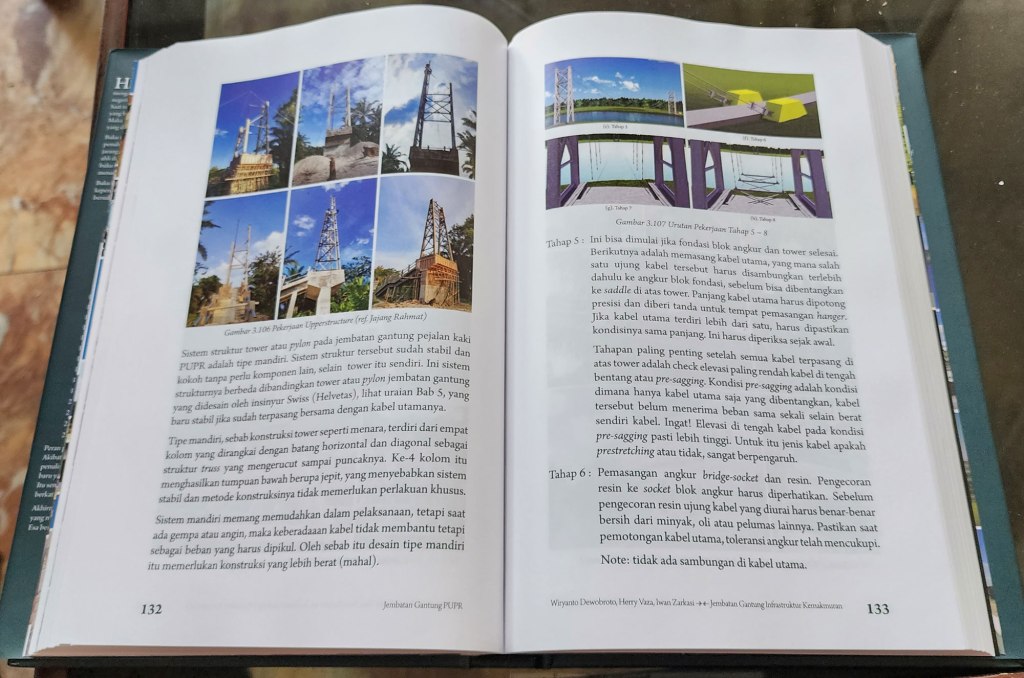
Tinggalkan komentar