Eh ternyata ada juga rekanku yang membaca ide tulisanku tentang UN di blog ini, sehingga ketika ketemu kemarin dengan canda menegur, “Ngapain sih pak Wir ngotot UN ? “. Padahal dalam sehari-harinya kita ini (aku dan temanku tersebut) tidak terlibat atau dilibatkan dengan UN, yang mana itu khan terjadinya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, di pendidikan tinggi khan belum tidak mengenal UN.
” Coba kalau ada semacam UN juga di tingkat perguruan tinggi, apa pak Wir juga mendukungnya ? “, demikian lanjut temanku tadi memberi semacam wawasan baru bagiku.
Aku berpikir lama dengan komentar temanku tadi, lalu aku membayangkan itu terjadi pada diriku, seolah-olah aku ini adalah seorang guru di sekolah. Guru yang telah merasa, memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Selama ini sebagai gurunya, akulah yang mengevaluasi kelulusan murid-muridku, pada mata pelajaran yang menjadi tanggung-jawabku. Jadi selama murid-murid tersebut rajin, yaitu selalu hadir dan mendengarkan / menyimak dengan baik materi yang kusampaikan, serta rajin mengerjakan tugas PR, maka pada umumnya pasti dapat lulus dengan baik. Bagaimana lagi, aku khan gurunya, yang tahu materi-materi yang telah diberikan dan dibahas, serta materi mana yang belum. Juga berdasarkan quiz-quiz yang kuberikan, aku jadi tahu bagian mana yang relatif mudah dan bagian mana yang relatif sukar bagi mereka. Jadi jika hal sama diberikan pada ujian akhir, yang menentukan kelulusannya, dan aku sebagai gurunya ingin agar mereka banyak yang lulus, maka tentu aku dapat memilih soal-soal apa yang cocok bagi mereka, sehingga probabilitas mereka untuk lulus adalah besar. Di sinilah aku menjadi paham ketika seorang guru yang lain dapat berkata dengan pede , bahwa ” para gurulah yang lebih tahu, siswa mana yang harus lulus atau siswa mana yang harus mengulang“. Benar juga.
Jadi jika terbukti bahwa banyak materi yang kuberikan juga keluar pada ujian akhir, maka para siswa banyak yang akan lebih menyimak pelajaran-pelajaran yang aku berikan. Itu berarti sebagai guru aku dihormati, karena kalau mereka melecehkan aku dan juga materi-materi yang kuberikan, maka bisa-bisa mereka tidak lulus sekolah. Itu khan masalah gawat bagi seorang murid.
Dengan kondisi seperti itu, aku menikmati menjadi guru. Ada nilai kepuasan yang tidak dapat ditukar dengan materi. Aku adalah GURU, diguGU dan ditiRU.
Jika kondisinya seperti itu, dan juga jika sekolah tempatku bekerja sudah dikenal orang dengan baik, misalnya sekolah favorit. Maka kondisi tersebut adalah kondisi yang ideal. Sebagai guru aku sudah dihormati murid-murid, dan sekolahnya sendiri sudah dianggap favorit oleh masyarakat, sehingga tidak takut tidak mendapat murid di tahun ajaran baru berikutnya. Pada kondisi yang ideal tersebut maka aku dapat bekerja dengan tenang sebagai guru mempertahankan kondisi tersebut, bertahun-tahun mendatang lamanya. Nggak perlu campur tangan orang lain untuk mendapatkan murid-murid bermutu, dan karena sudah favorit maka bantuan dari pemerintah bisa saja secara otomatis datang. Kenapa otomotis, karena jika pemerintah tidak membantu, maka jika sekolah berprestasi maka bisa-bisa dia punya kebijakan sendiri yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah, sumber dananya khan dari siswa. Sedangkan jika pemerintah membantu, minimal dia punya catatan prestasi. Ini lho peran pemerintah sehingga sekolah ini dapat berprestasi. He, he, pokoknya cocok dengan politik “citra” yang sekarang ini sedang laku keras bukan. 🙂
Kemudian, jika kondisi yang establish tersebut sekonyong-konyong digedor oleh perintah dari langit, dimana evaluasi kelulusan sekolah ditentukan dari luar, oleh pihak-pihak di luar guru-gurunya yang mengajar, seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu UN. Maka bagaimana rasanya.
Materi UN khan tidak dibuat oleh guru yang mengajar murid-muridnya sendiri, tetapi oleh team luar, yang para guru saja mungkin tidak tahu. Artinya, materi UN bisa-bisa tidak dipahami dengan baik oleh murid maupun gurunya. Untuk bisa tahu dan dapat menjawab dengan baik, maka siswa dan guru yang selama ini sudah baik-baik saja , perlu menyesuaikan diri lagi. Itu artinya murid dan guru perlu bekerja di luar dari apa-apa yang telah dilakukan selama ini. Kerja ekstra.
Jika aku sebagai guru, ngotot, tidak mau tahu dan tetap pada kebiasaanku yang ada, maka bisa-bisa apa-apa yang kuajarkan selama ini tidak berguna lagi, karena tidak sesuai dengan materi UN tersebut. Jika itu terbukti, dan diketahui oleh murid-muridku, maka bisa-bisa nanti mereka akan melecehkan. Untuk apa belajar dariku, gurunya, toh tidak akan keluar pada UN.
Jika itu terjadi, maka bisa-bisa mereka tidak akan menghormat aku lagi. Rasa puas, atau bangga yang aku terima selama ini bisa hilang tak berbekas.
Jika aku bekerja di luar dari apa-apa yang telah dilakukan selama ini, itu khan berarti kerja ekstra, itu juga berarti aku harus belajar lagi, menguasai materi UN. Jadi statusnya sama seperti murid-muridku, namanya saja belajar, apakah itu murid atau guru, berarti perlu effort khusus. Bayangkan, aku di sekolah sudah bekerja, mengajar murid-murid, pulang ke rumah ketemu anak dan istri, selain itu badan juga sudah tua. Jadi dengan demikian kapan waktu belajarnya. Artinya belajar lagi bagi seorang guru adalah suatu beban.
Bahkan yang lebih menakutkan bagi profesi guru adalah karena dengan adanya UN maka secara tidak langsung guru seniornya dievaluasi juga. Seperti misalnya jika aku guru matematik senior, ketika nilai UN keluar dan ternyata banyak murid-murid sekolah tersebut nilainya jelek, maka orang akan melihat pertama kali kepada gurunya, jika mata kuliah tersebut diajar oleh kelompok guru maka yang dilihat adalah yang seniornya. Itu khan bikin dag-dig-dug juga.
Dengan cara berpikir sebagai seorang guru seperti itu, aku jadi memahami mengapa banyak guru yang menolak UN. Apa untungnya hayo.
Jadi kalau begitu pak Wir masih ngotot dengan UN ?
<<< he, he, mikir dulu deh >>>




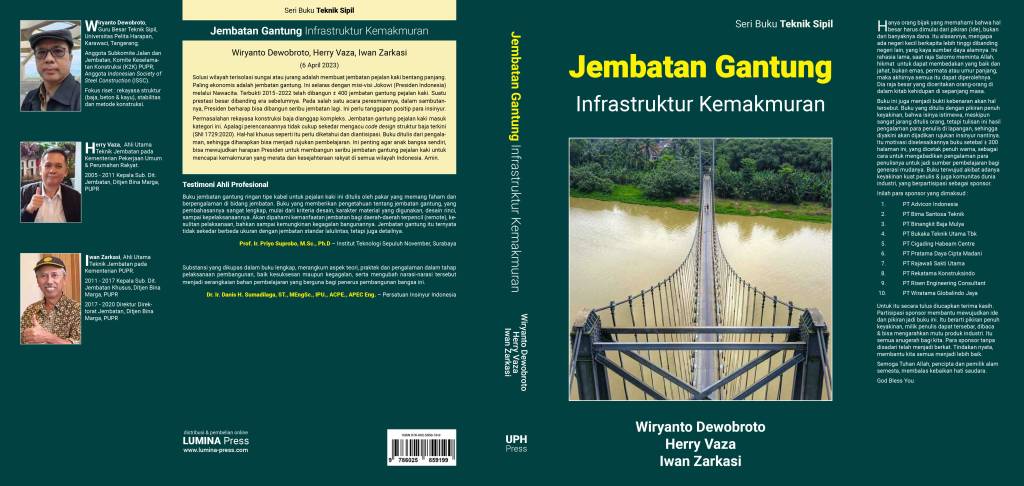


Tinggalkan Balasan ke goldfriend Batalkan balasan