SNI baja terbaru di Indonesia adalah SNI 1729:2015, yang merupakan adopsi utuh dari AISC 360-10. Nah terkait hal itu, mbak Hanna Yuni Hernanti dari Puslitbang PUSKIM di Cileunyi, Bandung, mengirimkan dokumen pendukung lain yang baru, yaitu Petunjuk Teknis Penggunaan SNI 1729Tentang Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. Dokumen tersebut sejatinya adalah terjemahan dari Design Examples Version 14.1 dari AISC.
Adanya buku petunjuk teknis yang baru di atas menunjukkan bahwa keputusan untuk mengadopsi code AISC adalah telah bulat. Itu berarti semua perencanaan gedung baja di bawah tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mengacu pada AISC yang merupakan sumber rujukan utama dari SNI kita.

Oleh sebab itu, materi pengajaran Struktur Baja di perguruan tinggi, harus menyesuaikan. Ini penting karena dalam praktiknya, masih banyak dosen yang mengajarkan metode ASD yang lama (AISC 1989). Alasannya masih banyak fabrikator baja yang memakai code tersebut, dibanding code baja yang terbaru (AISC 2010).
Bagi orang awam, alasan di atas tentunya dapat dianggap sebagai alasan yang masuk akal. Tetapi bagiku, tentunya tidak demikian halnya. Menurutku, itu seperti membandingkan antara apel dan jeruk. Bagaimana tidak, insinyur yang bekerja sebagai dosen (gurunya insinyur) tentunya berbeda dengan insinyur yang bekerja di fabrikator baja.
Bagi seorang dosen, agar bisa disebut sebagai guru, adalah penting untuk memberikan yang terbaik, yang state of the art, atau ilmu yang terbaru bagi murid-muridnya. Maklum, sifatnya adalah pendidikan dan pembelajaran, sehingga dianya harus juga memberi teladan bagi murid-muridnya dengan selalu belajar dan menggali ilmu baru. Kondisi itu tentunya berbeda dari seorang insinyur yang bekerja di fabrikator. Tugas utama fabrikator adalah memproduksi konstruksi baja secara aman tetapi ekonomis. Kalau diperlukan pembelajaran tentu tujuannya agar diperoleh keamanan yang dimaksud, dan tetap ekonomis. Jadi yang penting tentunya adalah profit setinggi-tingginya. Cara yang digunakan, bukanlah tujuan. Artinya, jika pakai cara lama masih bisa memberikan profit yang dimaksud, mengapa harus pakai cara baru. Iya khan ?
Jadi jika secara formil sudah diketahui bahwa sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan code yang harus dirujuk, maka seorang dosen, yang notabene gurunya insinyur, maka tentunya perlu melakukan penyesesuaian materi yang diajarkan. Jika tetap ngotot pakai materi lama, dengan alasan bahwa ilmu yang diajarkan masih dipakai oleh praktisi. Itu khan sebenarnya dosennya malas untuk up-dated ilmu yang terbaru. Maklum untuk belajar hal yang baru memang perlu enerji khusus.
Pak Wir ini bagaimana, mengapa ASD dianggap kuno. Bukankah di AISC 360-10 (2010) juga memuat cara tersebut lagi. Pada code AISC 2010 tersebut, kita bisa memilih cara perencanaan, apakah mau LRFD atau ASD. Gimana itu pak ?
Nah yang bertanya seperti ini pastilah belum membaca buku karyaku yang terbaru. Termasuk juga belum atau tidak mau membaca secara teliti code AISC 2010 tersebut.
Memang betul AISC (1989) dan AISC (2010) keduanya memuat kata ASD. Tetapi jangan terkecoh, kepanjangan dari keduanya adalah berbeda. ASD yang lama adalah kepanjangan dari Allowable Stress Design, adapun ASD yang baru adalah kepanjangan dari Allowable Strength Design. Sama-sama S, tetapi yang satu stress, sedangkan yang lain adalah strength. Beda banget itu.
ASD yang lama (1989) adalah perencanaan berdasarkan kondisi tegangan elastis material baja. Pada kondisi ini, tidak ada tinjuan adanya penampang plastis atau tidak. Maklum, karena untuk itu ada kententuan tersendiri, yang disebut analisis plastis. Adapun ASD yang baru (2010) adalah perencanaan berdasarkan kondisi ultimate penampang. Itu berarti sudah memperhitungkan adanya momen plastis pada penampang atau tidak.
Jadi praktisnya, dengan ASD lama, para perencanaan belum bisa memprediksi tentang perilaku struktur, apakah daktail atau tidak karena tidak membahas sampai terjadi momen plastis pada penampangnya. Adapun dengan ASD baru, karena pada dasarnya sama dengan cara LRFD, yaitu cara ultimate, maka dalam tahap perencanaannya sudah dapat diketahui kondisi keruntuhan elemen yang direncanakan, apakah bersifat daktail atau tidak.
Kemampuan memprediksi perilaku keruntuhan struktur, apakah daktail atau tidak , sangat penting dalam perencanaan bangunan tahan gempa. Itu salah satu alasan mengapa metode perencanaan modern adalah didasarkan perencanaan cara ultimate tersebut.
Pak Wir, jika ASD baru dan LRFD dapat dianggap sebagai cara ultimate. Lalu dimana perbedaan keduanya ?
Perbedaannya adalah pada momen / gaya perlu dan momen /gaya tersedia. Pada LRFD maka momen / gaya perlu adalah dikalikan dengan faktor beban, yang berbeda-beda untuk setiap kasus beban. Lalu di bagian momen / gaya tersedia dikalikan dengan faktor reduksi atau faktor ketahanan yang kita kenal sebagai phi. Adapun pada ASD, maka pada momen / gaya perlu tidak perlu dikalikan dengan faktor beban. Hanya saja, pada momen / gaya tersedia perlu dibagi dengan safety faktor atau omega. Itulah mengapa, dalam satu buku yang sama, yaitu AISC 360-10 dapat diberikan dua metode, yaitu ASD dan LRFD sekaligus. Itu sebenarnnya hanya untuk mengecoh agar para praktisi mau beralih dari ASD (lama) ke ASD (baru). Kesannya, tidak terlalu banyak usaha dibanding jika dari ASD ke LRFD. Gitu . . .
Nah bagi dosen Struktur Baja yang berminat untuk up-dated materi perkuliahan ke yang paling state of the art, yaitu yang mengacu SNI 1729:2015 atau AISC 2010, maka ada baiknya mengacu pada buku merah pada foto berikut.

Sampai saat ini, buku di atas adalah satu-satunya buku teks berbahasa Indonesia yang telah mengacu pada SNI 1729:2015 atau AISC 2010 yang terbaru.
Materinya disusun sudah mencakup 98% untuk proses pembelajaran di S1, yaitu mata kuliah Struktur Baja I, II dan III. Yang belum tercakup, adalah materi analisis plastis.
Untuk membelinya, silahkan order via on-line di http://lumina-press.com.




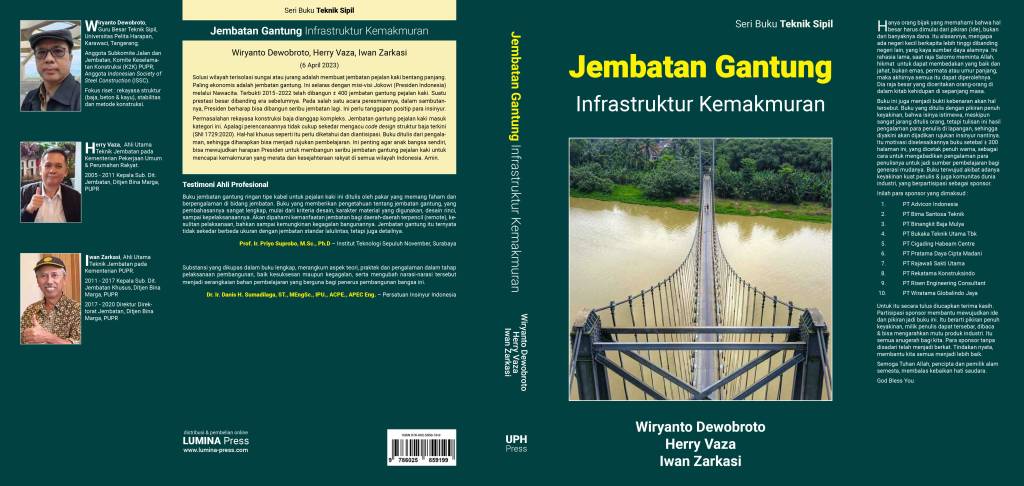

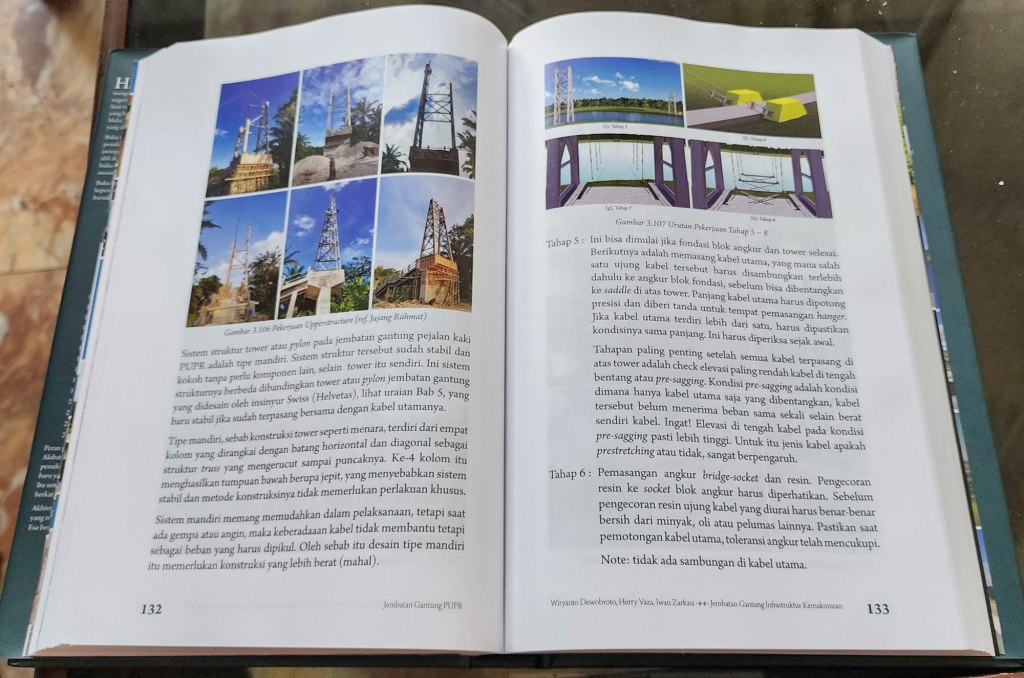
Tinggalkan komentar