Meskipun dididik , ditraining dan dihidupi dengan kompetensinya dibidang rekayasa (civil engineering, computer programming) tetapi tidak menganggap bahwa bahasa adalah sesuatu yang sepele, bahkan mempunyai pemikiran bahwa pelajaran berbahasa itu lebih penting dari pelajaran matematika. Begini maksudnya, jika seseorang disuruh memilih pertama-tama kali dalam hidupnya, pelajaran mana yang harus dikuasai terlebih dahulu maka dipilihlah bahasa yang utama, baru setelah itu yang lainnya.
Jadi saya termasuk salah satu engineer yang berpikir bahwa penguasaan bahasa adalah sangat penting, sangat berguna karena satu-satunya cara untuk mengungkapkan ide atau opini yang dipunyainya. Bahkan selalu getol mengajak mahasiswa, engineer dan orang lain untuk mempraktekkan kemampuan berbahasa tadi dengan sering menulis, misal ini, ini, ini juga setiap hari diusahakan untuk mempunyai kebiasaan menulis di blog ini. Ya seperti ini.
Meskipun demikian melihat kebijaksanaan-kebijaksanaan berbahasa yang ada di negeri ini saya cukup prihatin.
Mengapa ?
Kita lihat bagaimana usaha departemen pendidikan, dengan lembaga ikip-nya, berusaha mencetak guru-guru bahasa Indonesia, dan agar mereka mendapat lapangan pekerjaan maka kurikulum di tingkat pendidikan menjadi suatu yang utama, sejak SD, SMP, SMA (yaitu 12 tahun) bahkan sekarang ingin mengambil porsi perguruan tinggi (3 sks) bahkan bidang engineering sekalipun. Latar belakang mereka karena kita berbangsa, dan bernegara Indonesia yang cinta negeri ini maka mengikuti pelajaran bahasa Indonesia adalah WAJIB. Mengenai bidang ilmu itu sendiri. Wah gampang, itu nanti lah. Emangnya penting ?
Itu satu sisi yang kita lihat di tingkat pendidikan. Sorry, saya tidak menyalahkan guru-guru Bahasa, karena saya juga guru, jadi saya nggak mau jeruk makan jeruk . Ok. 😀
Tapi di sisi lain, melihat produk budaya bahasa kita, mulai dari iklan-iklan, juga tabloid-tabloid yang beredar. Saya sering melihat tulisan berbahasa Indonesianya seperti nulis sms, juga tidak kalah ramainya adalah sekarang sering beredar novel-novel remaja dengan bahasa gaul-nya. Asal nulis, tetapi karena gaul maka banyak yang beli. O ya, perlu ditambahkan, bahwa materi berbahasa yang diterbitkan dan dijual di toko-toko buku kebanyakan adalah produk dari budaya masyarakat yang notabene di luar pendidikan itu. Sedangkan dari yang dari pendidikan sendiri, jarang menelurkan produk sebuah buku yang sifatnya mencerahkan. Ada juga sih buku-buku yang diterbitkan dari kalangan pendidik tersebut, tapi isinya instruksional, kaku jadi males, kecuali jika itu disyaratkan guru / dosen sebagai materi ujian.
Jadi tidak adanya link-and-match antara teori (di dunia pendidikan) dan praktek (di dunia nyata) maka jelaslah meskipun para lulusan ikip tersebut ngotot mengajarkan bagaimana berbahasa yang baik maka ya seperti ini hasilnya.
Terus terang aku bisa produktif dalam menulis ini setelah lama lulus dari SMA koq. Saya sendiri lupa, apa waktu di UGM dulu juga belajar bahasa Indonesia. Rasanya tidak. Tapi buktinya bisa nulis juga ya.
Jadi sebenarnya menurutku agar bangsa ini mampu dan bangga berbahasa Indonesia maka strategi kebijaksanaan berbahasa tidak hanya tanggung jawab mendiknas aja, harus terintegrasi penuh dengan yang lainnya. Bahkan kalau perlu ada sistem pengawasan di penerbitan atau semacamnya, bagaimana produk yang dikeluarkan.
Jika itu tidak ada, dengan alasan kebebasan berpendapat, maka nggak ada gunanya ngotot menjelaskan kaidah-kaidah perbahasaan di tingkat pendidikan kita. Toh kalau di luar itu nggak laku. Bahkan ada pendapat bahwa memakai bahasa asing lebih keren. Dengan memaksanya sebagai salah satu kurikulum muatan wajib, khususnya di tingkat pendidikan lanjut, maka content kompetensi yang seharusnya dipunyai oleh seorang lulusan S1 jadi berkurang, ujung-ujungnya alumni kita tidak berkompeten di dunia profesional, kecuali memang kompetensi yang diambil memang berkaitan dengan komunikasi atau bahasa gitu lho.
Ya, itulah keprihatinanku dengan kondisi berbahasa di negeri ini.




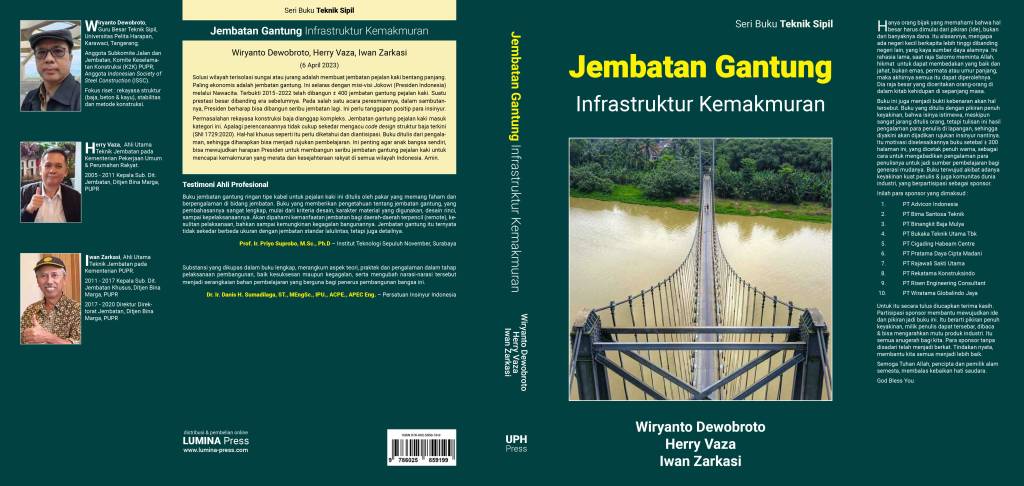


Tinggalkan komentar